*Mata-Mata Kolonial dan Identitas Semu: Menelusuri Jejak Imigran Yaman dalam Sejarah Nasionalisme Indonesia*
Oleh: Team Redaksi walisongobangkit.com
Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda menghadapi tantangan besar: menstabilkan kawasan Nusantara yang porak-poranda oleh perlawanan masif pribumi. Solusi yang diambil tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga bersifat sosial-struktural. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengimpor komunitas Arab dari Hadhramaut, Yaman, pada 1832, dengan fasilitas logistik disediakan oleh otoritas Belanda. Inilah cikal bakal kehadiran kelompok Ba’alwi di Indonesia—kelompok yang kelak akan memainkan peran krusial namun ambigu dalam lanskap politik dan sosial kolonial.
*Kapiten Arab: Struktur Kolonial Berkedok Representasi*
Dalam sistem administrasi kolonial, Belanda menerapkan kebijakan segregatif terhadap kelompok-kelompok etnis non-pribumi. Sebagaimana etnis Tionghoa memiliki “Kapiten Cina”, komunitas Arab juga diberi jabatan serupa, yakni “Kapiten Arab.” Jabatan ini konon ditujukan untuk mempermudah koordinasi, namun fungsinya lebih mirip instrumen kontrol sosial. Kapiten Arab bukanlah pemimpin yang lahir dari dinamika internal komunitas, melainkan perpanjangan tangan penguasa kolonial. Posisi ini dimanfaatkan Belanda untuk memantau, menyusup, dan jika perlu, mengintervensi dinamika sosial-keagamaan komunitas Arab.
*Nasab dan Legitimasi Politik: Klan Ba’alwi dan Restu Kolonial*
Klaim nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW menjadi kartu truf (modal utama) klan Ba’alwi dalam meraih status sosial di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Klaim ini bukan sekadar legitimasi keagamaan; ia adalah alat politik. Belanda dengan cermat menangkap peluang ini. Alih-alih mencurigai klaim tersebut, Belanda justru mendukung dan melegitimasinya. Dengan restu penguasa kolonial, klan Ba’alwi tidak hanya mengukuhkan kedudukan mereka di mata umat Islam lokal, tetapi juga mendapatkan perlindungan kekuasaan kolonial yang menghendaki stabilitas melalui ko-opsi simbolik.
*Konflik Horizontal: Fragmentasi Komunitas Hadhrami*
Namun dominasi Ba’alwi tidak tanpa perlawanan. Komunitas Hadhrami di Indonesia tidak homogen. Ketegangan antara kelompok Ba’alwi dan non-Ba’alwi, terutama kelompok Masyayikh (ulama non-sayyid), menciptakan konflik horizontal. Persaingan terjadi dalam memperebutkan kepercayaan masyarakat lokal, posisi keagamaan, bahkan akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Sumber konflik utamanya adalah klaim superioritas nasab, yang dianggap sebagian pihak sebagai bentuk feodalisme rohani yang tidak relevan dalam konteks keislaman egaliter.
*Sumpah Pemuda dan Ambivalensi Nasionalisme Arab*
Pada momen penting Sumpah Pemuda 1928, komunitas Arab tak menampakkan keterlibatan aktif. Keputusan sebagian tokoh muda keturunan Arab untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI) pada 1934 lebih merupakan respons terhadap tekanan sosial yang makin menuntut integrasi. Meskipun PAI menyatakan kesetiaan terhadap Indonesia, pendiriannya justru mengukuhkan segmentasi etnis dan menegaskan eksklusivisme identitas. Dalam catatan sejarah, PAI juga muncul sebagai reaksi atas dominasi kelompok Ba’alwi di kalangan Arab Indonesia itu sendiri, bukan semata demi nasionalisme.
*Nasionalisme yang Tertunda: Status Kewarganegaraan dan Integrasi Politik*
Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh penduduk Nusantara untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun banyak di antara imigran Yaman, termasuk sebagian besar dari klan Ba’alwi, tidak segera mendaftarkan diri sebagai WNI. Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana komitmen mereka terhadap cita-cita kebangsaan Indonesia? Sementara para pejuang dari berbagai suku dan agama mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan, sebagian kelompok Arab tampak ragu untuk melepaskan identitas transnasionalnya demi loyalitas terhadap Indonesia.
*Indikasi Absennya Nasionalisme*
Beberapa indikator memperkuat kesan bahwa sebagian komunitas Hadhrami, khususnya yang berada di bawah hegemoni Ba’alwi, menunjukkan sikap ambivalen terhadap semangat kebangsaan:
- Tidak tercatat keterlibatan aktif mereka dalam perjuangan bersenjata melawan kolonialisme.
- Klaim eksklusif sebagai keturunan Nabi digunakan untuk menjustifikasi superioritas sosial.
- Lambatnya adopsi status kewarganegaraan Indonesia.
- Pendekatan segregatif dalam organisasi seperti PAI, yang muncul terpisah dari arus utama nasionalisme multietnis dan multikultural.
*Penutup: Meninjau Ulang Peran Historis*
Narasi besar sejarah Indonesia tidak pernah tunggal. Dalam konteks ini, penting untuk secara kritis meninjau ulang peran komunitas imigran Yaman, khususnya klan Ba’alwi, dalam perjalanan bangsa. Mereka bukan semata kelompok religius yang menyebarkan Islam, tetapi juga aktor-aktor sosial-politik yang memiliki agenda tersendiri—kadang bersesuaian, kadang bertentangan dengan semangat nasionalisme. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang berdiri atas dasar keadilan sejarah, maka narasi-narasi dominan semacam ini perlu dikaji ulang dengan kaca mata ilmiah, bukan mitos genealogi.
*Referensi*
- Harapan Rakyat, “Kapiten Arab di Indonesia: Mandor Asing yang Disegani Belanda”
- Tirto.id, “Apa Itu Nasab Ba’alawi?”
- Merdeka.com, “Bersatunya Etnis Arab di Indonesia”
- Hidayatullah.com, “Sadah Ba’alawi dan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia”
- Wikipedia Indonesia (Kapiten Arab, Persatuan Arab Indonesia, Sumpah Pemuda Keturunan Arab)
- YouTube: Walisongo Bangkit, “Belanda Bawa Imigran Yaman ke Indonesia Tahun 1832”
- Liputan6.com, “Polemik Nasab Habib Ba’alwi Mulai Dapat Dukungan Kiai di Garut”
- Bojonegoro.com, “Akar Konflik Ba’alwi: Akademis atau Etis?”
- Katalog Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya
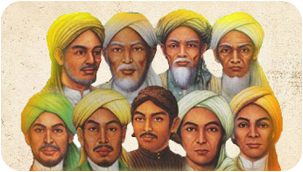

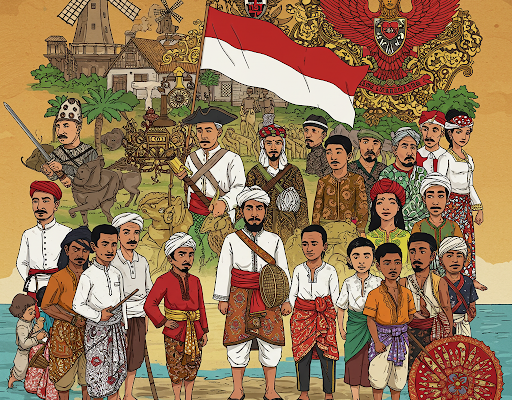


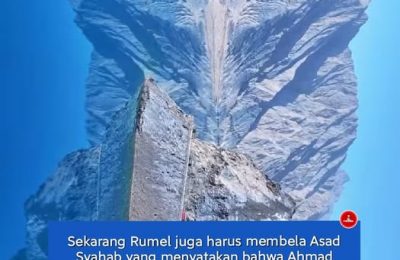






 Users Today : 742
Users Today : 742 Users Yesterday : 1099
Users Yesterday : 1099 This Month : 742
This Month : 742 This Year : 34875
This Year : 34875 Total Users : 667943
Total Users : 667943 Views Today : 1974
Views Today : 1974 Total views : 1543934
Total views : 1543934 Who's Online : 15
Who's Online : 15