Jejak Langkah yang Terlupakan: Tujuan Kedatangan Klan Ba’alwi di Hindia Belanda
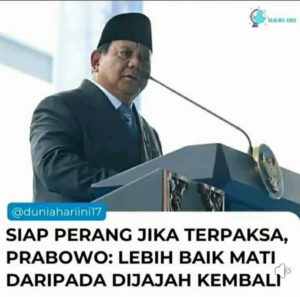
Masyarakat Indonesia hari ini perlu menengok ulang satu halaman sejarah yang kerap luput dari perbincangan arus utama: kedatangan kelompok Hadrami—khususnya yang dikenal sebagai Klan Ba’alwi—ke wilayah Nusantara pada abad ke-19.
Kedatangan mereka, berdasarkan sejumlah dokumen kolonial dan kajian ilmiah, tidaklah berdiri dalam ruang hampa. Sekitar tahun 1830, gelombang pertama orang-orang asal Yaman Selatan—khususnya dari wilayah Hadramaut—mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Sejumlah sejarawan, seperti Dr. Bernard Dahm dan Snouck Hurgronje, menyebut bahwa kelompok ini memiliki relasi khusus dengan administrasi kolonial. Mereka didatangkan bukan tanpa maksud.
Tujuannya? Menguatkan kontrol Belanda di wilayah-wilayah yang bergolak akibat perlawanan pribumi, terutama perlawanan yang dimotori oleh para kiai dan bangsawan lokal keturunan Walisongo di tanah Jawa. Dalam banyak kasus, kelompok Hadrami ini berperan sebagai agen stabilisasi sosial keagamaan. Sebagian didorong untuk menjadi ulama, sebagian lainnya diarahkan sebagai penghubung antara elite kolonial dan masyarakat Muslim.
Menjelang pergantian abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1900, gelombang kedua kedatangan terjadi. Kali ini, peran mereka lebih nyata dalam struktur kekuasaan. Catatan Residen Belanda menyebut sebagian dari mereka menjadi bagian dari angkatan keamanan kolonial, atau turut serta dalam struktur birokrasi yang mendukung status quo.
Agar lebih diterima oleh masyarakat, sejumlah tokoh Hadrami lantas mulai memperkenalkan diri sebagai “dzurriyah Rasulullah”—keturunan Nabi Muhammad SAW. Status ini mendongkrak penerimaan sosial mereka secara signifikan. Bahkan, pada beberapa dekade berikutnya, istilah “habib” atau “sayyid” menjadi simbol kesucian spiritual yang tak jarang membungkam kritik.
Namun, sejarah mencatat dinamika yang lebih kompleks. Setelah Indonesia merdeka, isu kewarganegaraan kelompok Hadrami sempat mengemuka. Pada awal 1950-an, pernah muncul wacana deportasi terhadap warga keturunan Arab yang belum mengurus status WNI. Para ulama NU seperti KH Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh dari pesantren Buntet Cirebon tampil membela, menyerukan asas ukhuwah Islamiyah. Pemerintah kala itu akhirnya mengakomodasi permohonan tersebut.
Namun, persoalan tak berhenti di sana. Dalam pidatonya tahun 1964, Presiden Soekarno kembali menyinggung soal identitas dan keberpihakan sejumlah kelompok yang dianggap tidak loyal terhadap cita-cita revolusi. Isu deportasi kembali mencuat, meski pada akhirnya tidak pernah diwujudkan secara menyeluruh.
Kini, dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi genetik, masyarakat mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru: benarkah klaim-klaim nasab yang diwariskan selama ini? Apakah benar terdapat hubungan biologis dengan Rasulullah SAW? Sejumlah hasil pengujian DNA yang dilakukan secara global terhadap komunitas-komunitas pengklaim nasab menyiratkan perlunya verifikasi ulang secara ilmiah dan independen. Kajian akademik yang dilakukan oleh pakar seperti Dr. Michael Hammer, Dr. Yehia Gad (Mesir), hingga Dr. Sugeng Sugiarto (Indonesia), menunjukkan bahwa klaim nasab bukan hal yang boleh diterima tanpa bukti empirik.
Lebih dari itu, muncul kritik sosial terkait sikap sebagian kecil anggota komunitas yang mengklaim garis keturunan mulia tersebut, namun justru dinilai tidak mencerminkan akhlak dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Sejumlah laporan menyebut adanya tendensi eksklusivisme, pengultusan status darah, hingga upaya memanipulasi narasi sejarah lokal.
Tentunya, hal ini tidak dapat digeneralisasi. Masih banyak individu dari kalangan Hadrami yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Namun, refleksi tetap diperlukan—terutama menyangkut bagaimana narasi keturunan digunakan dalam ruang publik, apakah untuk mengayomi atau justru untuk mendominasi?
Menolak klaim garis keturunan bukan berarti membenci pribadi atau kelompok tertentu. Ini soal akurasi sejarah, bukan soal kebencian. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk bersikap kritis, rasional, dan berbasis data, bukan sekadar takzim pada simbol-simbol.
Negara ini dibangun atas prinsip kesetaraan, bukan hierarki darah. Maka, siapa pun yang hidup dan mencari berkah di bumi Indonesia, perlu berjalan bersama sebagai warga bangsa yang setara. Tanpa perlu menyandarkan kehormatan pada nasab, melainkan pada akhlak, ilmu, dan kontribusi nyata.
Catatan Redaksi: Tulisan ini dimaksudkan sebagai refleksi historis dan ajakan kepada masyarakat untuk berpikir kritis terhadap narasi sejarah yang beredar. Kami mengedepankan pendekatan berbasis fakta, tanpa kebencian, dan menghormati keragaman dalam masyarakat Indonesia.
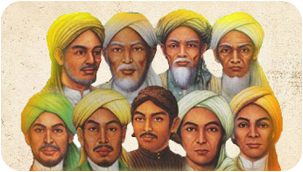




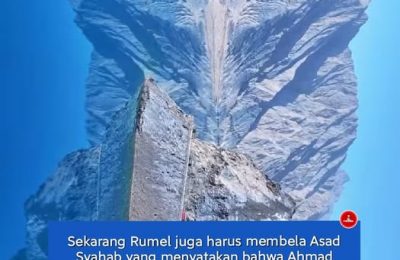





 Users Today : 523
Users Today : 523 Users Yesterday : 1099
Users Yesterday : 1099 This Month : 523
This Month : 523 This Year : 34656
This Year : 34656 Total Users : 667724
Total Users : 667724 Views Today : 1314
Views Today : 1314 Total views : 1543274
Total views : 1543274 Who's Online : 6
Who's Online : 6